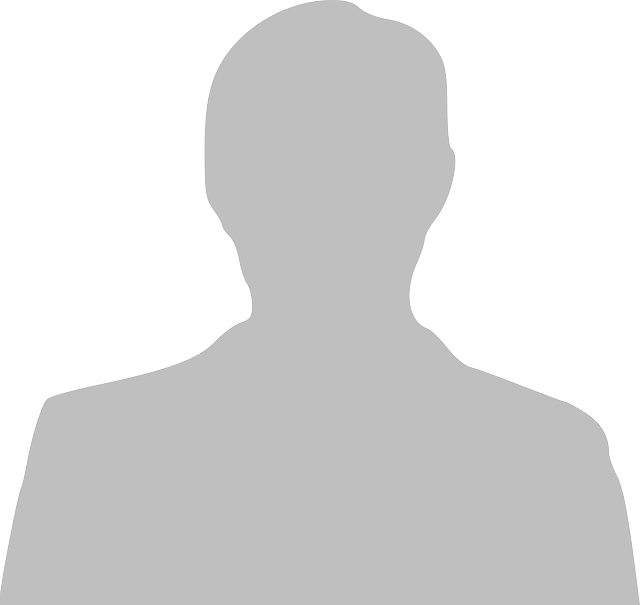KatoKito
Catatan dari Leiden, Belanda: Bukan Sekadar Lada dan Rempah, Ketika "To Live as Brothers" Mengalir dalam Darah
Oleh: Najmah* & Kusnan**
Membaca kembali To Live as Brothers karya Barbara Watson Andaya membawa imajinasi saya melayang ke abad ke-17 di tepian Sungai Batang Hari dan Musi, tempat saya dan suami saya dilahirkan dan dibesarkan. Di masa itu, leluhur kita dan orang-orang Belanda bernegosiasi, bersumpah setia, dan hidup berdampingan demi perdagangan.
Namun, menutup buku itu dan melangkah keluar rumah di hari ini, saya menyadari satu hal: narasi itu belum selesai. Ia hanya berubah wujud.

Gambar Buku To live as Brother karya Barbara Watson Andaya
Sehari-hari di Leiden, Belanda, saya dengan mudah bertemu teman-teman Belanda yang sekilas tampak sangat "Eropa", namun menyimpan cerita yang mengejutkan. Dalam obrolan santai di kedai kopi, perjumpaan di kampus, atau saat mengurus administrasi publik, kalimat-kalimat tak terduga sering meluncur begitu saya menyebut asal saya: "Indonesia, Sumatera."
Wajah Eropa, Jiwa Nusantara
Di kantor Gemeente (Balai Kota) Leiden, saat saya sedang mengurus BSN (Burgerservicenummer), seorang ibu berambut pirang menatap saya hangat; "Nenek saya orang Jawa Tengah,"
Kejutan serupa terjadi di International Institute for Asian Studies (IIAS), Universitas Leiden. Seorang staf dengan bangga menceritakan akar Sumateranya. katanya.
"Ibu saya orang Padang dan ayah saya orang Belanda," ujarnya tiba-tiba. Ia tersenyum, menunjuk rambutnya sendiri. "Ada darah Indonesia di sini. Secara genetik saya 80% Indonesia, lihat rambut saya hitam aslinya."
Bagi mereka, identitas bukan sekadar apa yang tertulis di paspor, melainkan memori yang hidup.
Luka Sejarah di Pasar Sabtu
Namun, di balik kehangatan sapaan itu, terselip narasi sejarah yang pedih. Perjumpaan-perjumpaan ini membawa saya pada masa transisi kemerdekaan Indonesia di era Presiden Soekarno, sebuah masa ketika garis batas kewarganegaraan ditarik dengan tajam.
Di Perpustakaan Universitas Leiden, seorang pustakawan bercerita dengan tatapan menerawang. "Kakek saya orang Belanda yang lahir di Surabaya. Setelah kemerdekaan, ia harus memilih. Akhirnya ia 'pulang' ke Belanda negeri yang sebenarnya asing baginya. Kakek mengarungi lautan selama satu bulan dan tiba di Rotterdam tahun 1950-an."
Kisah pilu lainnya saya temukan di Pasar Sabtu (Saturday Market). Saat saya membeli sambal terasi asli Sumatera Barat, sang penjual ujar pemuda 20 tahunan berambut pirang bercerita dalam Bahasa Inggris yang fasih namun dengan hati yang tertambat di tanah leluhur.
"Ayah saya asalnya dari Payakumbuh, menikah dengan Ibu saya keturunan Belanda," ujarnya sambil membungkus belanjaan Oma Sambal. "Saat kemerdekaan, Ayah dihadapkan pada dua pilihan sulit: menjadi warga Indonesia atau kembali ke Belanda. Dengan berat hati beliau meninggalkan Indonesia karena dianggap bukan pribumi setelah menikahi Ibu."Mereka inilah yang menyebut diri sebagai Indo (Indisch-Nederlanders).
Jembatan yang Hidup
Istilah "Indo" seringkali disalahartikan hanya sebatas label demografis bagi keturunan campuran Eropa dan pribumi, atau orang Eropa totok yang lahir besar di Hindia Belanda. Padahal, bagi saya, mereka adalah monumen hidup dari sejarah panjang interaksi kita.
Jika buku Barbara Watson Andaya mencatat bagaimana Sultan dan VOC mengikat janji persaudaraan lewat ritual minum "air sumpah" atau tukar-menukar keris, maka teman-teman "Indo" yang saya temui di Leiden ini adalah bukti fisik dari persaudaraan yang lebih intim.
Mereka adalah hasil dari pertemuan dua dunia yang tidak hanya terjadi di meja dagang Loji Belanda, tetapi juga di ruang-ruang privat rumah tangga selama beratus tahun.

Dari Payakumbuh Hingga Leiden
Yang paling menarik bagi saya adalah benang merah Sumatera. Jejak kolonial seringkali didominasi narasi Jawa, namun mendengar kalimat "Ibu saya orang Payakumbuh" atau "Ayah saya asli Padang" di tengah kota Leiden yang dingin, mengingatkan kita kembali pada era yang ditulis Andaya: bahwa Sumatera pernah menjadi kancah interaksi global yang intens.
Ketika menatap mata mereka, saya tidak lagi melihat "penjajah" atau "orang asing". Saya melihat refleksi dari nenek moyang kita sendiri. Di meja makan mereka, mungkin masih tersaji Rijsttafel, rendang, atau gulai, sebuah warisan rasa yang bertahan melintasi benua dan zaman.
Sejarah seringkali diajarkan sebagai deretan angka tahun dan perang. Tapi pertemuan-pertemuan kecil di Leiden ini mengajarkan saya bahwa sejarah adalah tentang manusia. Konsep "To Live as Brothers" (Hidup Sebagai Saudara) ternyata bukan sekadar jargon diplomasi abad ke-17 yang usang.
Ia adalah realitas biologis dan kultural hari ini. Kita memang pernah hidup berdampingan demi perdagangan lada dan rempah. Tapi kini, kita hidup berdampingan karena kita, dalam arti yang paling harfiah, adalah saudara jauh yang dipertemukan kembali.
Berdamai dengan Sejarah
Pada akhirnya, narasi sejarah tidak pernah benar-benar berhenti; ia hanya berganti rupa. Di balik dinginnya kota Leiden dan wajah-wajah "bule" yang asing, tersimpan kehangatan darah Nusantara yang mengejutkan. Mulai dari pegawai balai kota hingga pedagang pasar, banyak dari mereka adalah monumen hidup dari perjumpaan panjang nenek moyang kita.
Mereka adalah kaum "Indo" (Indisch-Nederlanders), anak-anak sejarah yang lahir dari transisi kemerdekaan yang menyakitkan. Kisah mereka bukan hanya tentang perpindahan demografis, melainkan tentang keterasingan, kerinduan, dan pilihan sulit antara dua tanah air.
Demikian juga Konsep "To Live as Brothers" (Hidup Sebagai Saudara) kini bukan lagi sekadar jargon diplomasi dagang VOC di tepian Sungai Batang Hari. Di abad ke-21 ini, konsep tersebut telah mewujud menjadi realitas biologis. Kita tidak lagi disatukan oleh lada dan rempah di meja loji, melainkan oleh DNA, sepiring rendang, dan memori kolektif yang menolak untuk mati.
Pertemuan di Leiden ini mengajarkan bahwa sejarah bukanlah tentang angka tahun, melainkan tentang manusia. Dan orang-orang yang kita temui di sana, dalam arti yang paling harfiah, adalah saudara jauh kita yang akhirnya dipertemukan kembali.
*Research Fellow International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden University Belanda & Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri
**Fakultas Ekonomi, Universitas IBA, Palembang