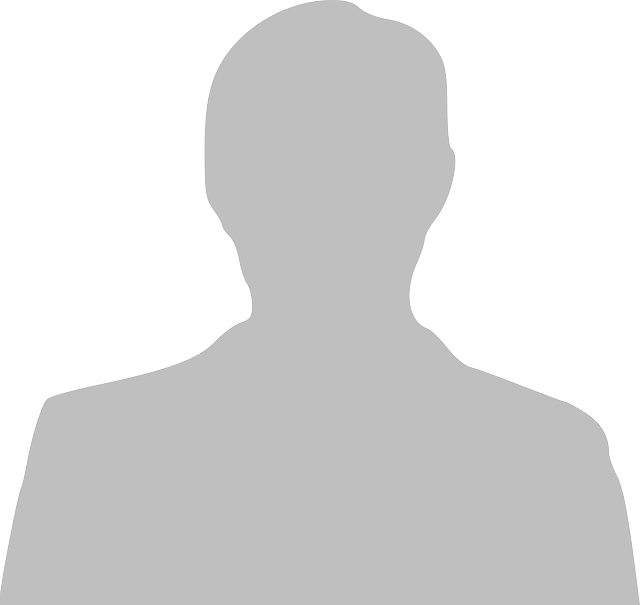BucuKito
Kisah Pengemudi Ketek: Mengadu Nasib di Atas Arus Sungai Musi dan Bertahan untuk Jaga Tradisi
Oleh: Tia Apriyani*
DI atas arus Sungai Musi yang tenang, menyimpan kisah getir, seorang pria paruh baya yang hingga kini masih setia mengemudi sebuah ketek atau perahu kayu sarana transportasi di perairan Sungai Musi, Palembang. Muhammad Yusuf namanya, sejak 1980 telah mengemudi ketek mengangkut penumpang yang biasanya menyeberang dari bagian hulu ke hilir Palembang pun sebaliknya.
Pada masanya, ketek adalah denyut nadi masyarakat Palembang. Orang-orang dari seberang hulu dan seberang hilir menyeberang ke Pasar 16 Ilir, menyeberang, mengangkut barang dengan menggunakan perahu kayu tersebut.
“Ongkosnya, sangat murah hanya berkisar Rp 300 per penumpang, ” ungkap Yusuf (68), dibincangi belum lama ini.
Namun, roda zaman berputar, karena mengemudi ketek tak bisa jadi diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Pada 1990, Yusuf sempat berhenti sejenak dari usaha ketek. Ia mencoba berdagang ikan, beradaptasi dengan situasi baru, sebab di tahun-tahun itu mulai terlihat tanda-tanda perubahan. Pelan tapi pasti, tradisi nyeberang ketek mulai tergerus oleh arus modernisasi.
Baca Juga:
- Didampingi BRI, UMKM Teh Bogor Kian Tangguh dan Tembus Rantai Pasok Global
- Txture Shoes: Dari Gang Kecil di Cibaduyut ke 33 Negara
- Gultik Blok M: Kuliner Legendaris Jakarta, Porsi Mini, Cita Rasa Maksimal
Tahun 2003 menjadi babak pahit dalam hidupnya. Ketika Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra melakukan penggusuran lapak sekitar Benteng Kuto Besak dekat Jembatan Ampera dan Pasar 16 Ilir.
Ia pun kembali menjadi pengemudi ketek. Seiring Waktu terjadi perubahan signifikan. Dulu, antrean penumpang di dermaga tak pernah putus. Kini, jarang sekali ada orang yang mau menyeberang menggunakan ketek.
"Transportasi online seperti ojek online makin menguasai kota. Pasar-pasar besar di daerah hulu dan hilir bermunculan, membuat warga tak perlu jauh-jauh lagi ke Pasar 16," ucap Yusuf.
Di tengah perubahan itu, pria ini tetap bertahan. Karena, ketek adalah penghidupan yang ia jalani selama ini. Tak ada pilihan lain. Mencari pekerjaan di sektor informal pun sulit. “Cukup dak cukup cukupke lah,” ucapnya pelan, menandakan bahwa bertahan adalah cara terbaik yang bisa ia pilih.
Andalkan Wisatawan
Kini, ketek lebih banyak dimanfaatkan saat hari libur sekolah atau di Waktu akhir pekan. Wisatawan yang ingin menyusuri Musi atau berkunjung ke Pulau Kemaro menjadi harapan terakhir.
Jika beruntung, satu kali perjalanan ke Pulau Kemaro bisa dihargai Rp 200 ribu. Tapi itu pun tak selalu ada.
“Kadang seharian dak dapat penumpang,” keluhnya.
Untuk sekali perjalanan wisata ke Pulau Kemaro, maksimal bisa mengangkut 10 orang dengan tarif Rp 200 ribu perjalanan pulang dan pergi.
Sementara untuk nyebrang ke 7 Ulu, tarifnya Rp 5 ribu per orang.
Ia menungkapkan kesedihannya, melihat tradisi tua itu perlahan sekarat.
Dulu, ketek menjadi transportasi andalan masyarakat kota Pempek, katanya.
Ia sempat berpikir untuk berhenti. Anak-anaknya sudah beberapa kali menyarankan agar ia beristirahat di rumah. Namun, hati kecil belum rela. Setiap hari, tubuh tuanya tetap menyusuri sungai, berharap ada satu-dua penumpang.
“Makan anak bisa bantu, tapi hidup ini perlu aktivitas,” katanya sambil tersenyum getir.
Upaya pemerintah daerah pun dirasakannya masih minim. Bantuan sosial hanya pernah diterima istri, berupa uang tunai Rp 1,6 juta sekali saja, serta bantuan beras.
Organisasi seperti PBM atau kelompok lansia pun jarang aktif mendampingi para pelaku usaha ketek.
Meski getir, harapan tak sepenuhnya padam. Yusuf bermimpi, andai pasar-pasar bisa disatukan kembali, mungkin tradisi nyebrang ketek dapat kembali hidup. Tapi ia juga paham, zaman terus berubah. Masyarakat lebih memilih kecepatan dan kenyamanan transportasi modern dibandingkan nostalgia menyeberang sungai.
Baca Juga:
- Pengisi Kekosongan Referensi Sejarah Palembang
- Dorong Guru SMK Sumsel Hadirkan Transisi Energi di Ruang Kelas
- Sriwijaya Economic Forum 2025, Bank Indonesia Sumsel Ajak Pemangku Kepentingan Diskusi Strategi Ketahanan Pangan
Dia bercerita, ketek yang dikemudikannya tersebut, dibeli seharga Rp 10 juta, hasil dari tabungan sedikit demi sedikit.
Sedangkan ketek besar dengan kapasitas lebih banyak dihargai Rp 25 juta per unit, angka yang kini sulit dicapai di tengah pemasukan yang tidak menentu.
Dari balik kemudi ketek tuanya, Yusuf terus menyimpan harapan sederhana, agar tradisi ketek ini bisa bertahan, diwariskan, dan mungkin suatu hari nanti diperhatikan pemerintah. Karena baginya, ketek bukan sekadar perahu, melainkan sejarah, identitas, dan harga diri warga Palembang.
Di sisa usia dan tenaganya, ia tak lagi mengejar kekayaan. Cukup bisa makan, memberi cucu jajan, dan tetap menyusuri Musi, itu sudah lebih dari cukup. Seperti keteknya yang terus berlayar, meski arus zaman terus mengalir deras ke arah sebaliknya.
*Mahasiswi Prodi Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang, Angkatan 2023