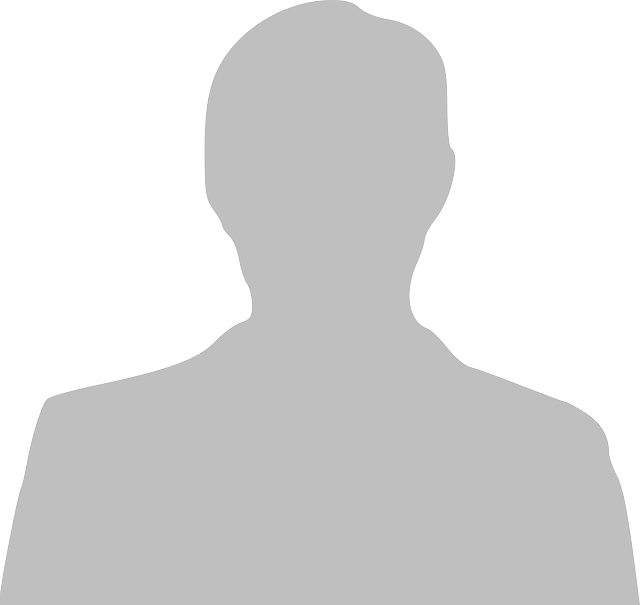KabarKito
Komitmen Iklim Indonesia di COP 30 Minim Keadilan Bagi Perempuan
JAKARTA, WongKito.co - Pidato resmi Indonesia di COP 30 yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, kembali menjadi sorotan. Solidaritas Perempuan menilai, pidato itu masih menunjukkan kecenderungan pendekatan teknokratis, maskulin dalam kebijakan iklim nasional dan abai terhadap dimensi keadilan sosial dan gender.
“Pidato ini gagal mengakui bagaimana perempuan, hususnya perempuan nelayan, petani, masyarakat adat, dan buruh migran dan subjek rentan lainnya, menanggung beban paling berlapis dari dampak krisis dan proyek iklim,” tulis Solidaritas Perempuan dalam keterangan resmi yang diterima Minggu (09/11/2025).
Alih-alih menempatkan mereka sebagai subjek utama dalam transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam dalam mengatasi krisis iklim, pemerintah justru menonjolkan proyek-proyek besar seperti nuklir, biofuel, dan waste-to-energy yang berpotensi memperkuat ketimpangan dan pemiskinan sistemik melalui mempersempit ruang hidup perempuan di akar rumput.
Komitmen yang ditunjukkan pun tidak lebih sebagai ajang berjualan karbon yang ke depannya hanya akan menguntungkan korporasi-korporasi pencemar lingkungan dan memperparah krisis iklim.
- Pameran Arsip KERTAS: Setara, Merekam Perempuan dalam Ruang Demokrasi
- Simak 9 Cara Menjadi Penulis Freelance Tanpa Pengalaman
- Beli Mobil di TAG Akhir Tahun Ini, Bisa Dapat Hadiah Umroh atau Liburan ke Turki!
Dalam pidato Indonesia di COP 30 pun hanya menyinggung perempuan secara sekilas dalam kategori “kelompok rentan”, tanpa menyebutkan strategi implementasi Gender Action Plan (GAP) yang menjadi mandat internasional sejak COP 23 di Bonn dan diperkuat pada COP 28.
Padahal Indonesia belum memiliki Gender Action Plan (GAP) yang jelas, terukur, dan disahkan secara lintas kementerian. Dokumen ini seakan hadir hanya sebagai pelengkap untuk pemerintah berdagang di COP 30.
Ketua Badan eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi menegaskan, Indonesia menekankan bahwa aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada masyarakat terutama kelompok rentan. Namun di sisi lain, Negara ambisius melakukan penurunan emisi melalui hilirisasi pertumbuhan ekonomi hijau melalui pendekatan ekstraktif, yang mengedepankan proyek energi skala besar seperti geothermal , PLTA, hingga PLTB di berbagai wilayah seperti Pocoleok, Lampung, Aceh hingga Sulawesi Tengah.
Proyek adaptasi iklim juga digenjot seperti food estate (cetak sawah) di Kalimantan Tengah hingga infrastruktur bendungan/DAM di Nusa Tenggara Barat, telah mengurai fakta dampak deforestasi, perampasan tanah, dan hilangnya sumber penghidupan perempuan.
"Tanpa Gender Action Plan yang kuat, dan diintegrasikan dalam seluruh kebijakan dan aksi iklim, Pemerintah Indonesia hanya omon-omon dan akan memperluas ketidakadilan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Pemerintah mengklaim bahwa tingkat deforestasi menurun 75% sejak 2019. Namun, fakta di lapangan, ekspansi industri sawit, tambang nikel, dan proyek energi terus menggusur hutan dan lahan hidup perempuan.
Contoh kasus yang yang ditemukan oleh Solidaritas perempuan, yang dimuat pada Laporan Penelitian Aksi Berperspektif Feminis (FPAR) tahun 2015, proyek percontohan REDD di Kalimantan Tengah, telah berdampak terhadap perempuan di wilayah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek yang didukung dengan pendanaan sebesar 30 juta dollar AUS dari program Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) tersebut membuat pembatasan akses masuk ke hutan dan informasi bagi perempuan untuk memahami proyek ini.
Tak hanya itu, mekanisme Perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 yang membentuk arsitektur pasar karbon nasional berbasis digital dan Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan standar internasional terkemuka seperti Verra, Gold Standard, Plan Vivo, dan Global Carbon Council (GCC) melalui program REDD+ justru akan semakin meminggirkan peran perempuan dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya alam serta memutus relasi holistik perempuan adat dalam melestarikan lingkungan dan kearifan lokal.
- Kolaborasi Lintas Unit: Rektor Unsri, Luncurkan 2 Buku Internasionalisasi
- AJI Indonesia-Koalisi Masyarakat Sipil Bersatu Dukung Tempo Melawan Gugatan Rp200 Miliar oleh Mentan Amran Sulaiman
- Ivonne Setiawati dari Kebun Buddhi, Ajak Masyarakat Olah Sampah jadi Bernilai Ekonomis dengan Biowas Promic
Pernyataan Indonesia yang menyebut bahwa “aksi iklim harus inklusif dan berpusat pada manusia” juga menjadi lip service belaka jika tidak diikuti dengan kebijakan konkret yang mengakui hak dan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan.
Hal ini diperlihatkan dari bagaimana kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran masih sangat maskulin yang didominasi oleh laki-laki, dari 53 Kementerian hanya 2 Kementerian yang dipimpin oleh perempuan dan tidak pada posisi strategis dalam isu-isu kerusakan ekologis dan krisis iklim.
Oleh sebab itu, Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa krisis iklim tidak dapat diselesaikan hanya dengan target angka dan teknologi. Solusinya harus dimulai dari pengakuan atas pengalaman dan kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas karena mereka lah yang merasakan dampaknya secara langsung. (*)