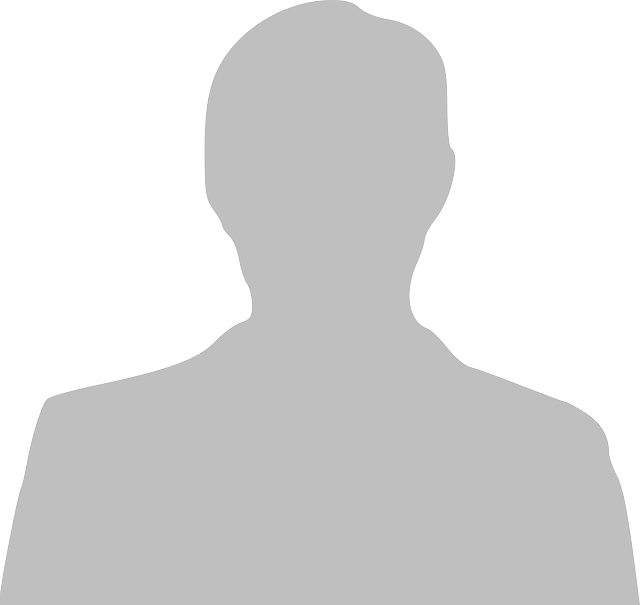BucuKito
Mengenal Situs Ki Gede Ing Suro, Candi yang Jadi Makam Raja
Di balik gang sempit di Kelurahan 1 Ilir Palembang berdiri sebuah gapura beratap seng merah tua. Tak banyak yang tahu, di balik pagar hijau itu terdapat candi dari masa pasca Sriwijaya yang kini menjadi makam raja-raja Islam.
Memasuki kawasan tersebut, pengunjung akan menjumpai pemakam Ki Gede Ing Suro yang terbuka tanpa atap dan dinding. Struktur candinya langsung berhadapan dengan panas dan hujan. Sebagian pelataran telah beralas semen dan bata, sementara bagian lainnya ditumbuhi rumput hijau yang terawat dan pot-pot bunga dari semen. Tampak cantik dan rapi, meski di beberapa sisi terlihat retakan dan bekas kerusakan.
Beberapa pohon besar tumbuh rindang di dalam area pemakaman, menjadi tempat berteduh dari terik matahari. Di sekeliling bangunan candi, jalan setapak dari susunan bata dibuat rapi agar aman dilalui pengunjung. Pada setiap sisi tubuh candi, masih tampak ukiran relief yang menjadi penanda kuat peninggalan masa lalu.
Jauh sebelum menjadi makam, bangunan ini berdiri sebagai candi tempat ibadah masyarakat pada abad ke-14, ketika pengaruh Hindu–Budha masih kuat, meskipun Kerajaan Sriwijaya telah runtuh. Keyakinan masyarakat tidak serta-merta berubah. Candi tetap dibangun dan dipandang sebagai ruang suci.
Perubahan terjadi ketika Islam mulai diterima oleh masyarakat. Candi-candi tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah, namun tetap dihormati sebagai lokasi yang sakral. Ketika Kerajaan Palembang yang bercorak Islam berdiri, tempat-tempat suci inilah yang kemudian dipilih sebagai lokasi pemakaman para raja.
Dari sinilah, situs Ki Gede Ing Suro mengalami perubahan fungsi. Dari candi Budha menjadi makam raja-raja Islam, tanpa menghilangkan bentuk bangunan aslinya.
“Ini adalah contoh nyata bagaimana candi Budha dipergunakan ulang sebagai makam raja-raja Islam,” ujar pendiri komunitas Sahabat Cagar Budaya Palembang, Robby Sunata saat dibincangi, Kamis (22/01/2026).
Siapa Ki Gede Ing Suro?

Di antara deretan makam yang berada di atas struktur candi, nama yang paling dikenal adalah Ki Gede Ing Suro Muda, raja kedua Kerajaan Palembang yang telah memeluk Islam. Ia merupakan keponakan dari Ki Gede Ing Suro Tua, raja pertama kerajaan tersebut.
Berbeda dengan sang keponakan, Ki Gede Ing Suro Tua justru tidak dimakamkan di kawasan ini. Hingga kini, lokasi makamnya belum diketahui secara pasti, seolah menyisakan satu potongan sejarah yang belum terjawab.
Ki Gede Ing Suro sendiri dikenal berasal dari Jawa dan berangkat ke Palembang melalui pelabuhan Surabaya. Namun, secara garis keturunan, leluhurnya merupakan orang Palembang. Kisah ini berkaitan dengan Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak, yang diketahui lahir dan besar di Palembang hingga usia sekitar 19 tahun sebelum pergi ke Jawa untuk belajar Islam kepada Sunan Ampel.
Setelah Kesultanan Demak berdiri, terjadi konflik internal dalam keluarga kerajaan. Pihak yang kalah kemudian menyingkir ke Surabaya, lalu ke Palembang. Dari garis keturunan inilah muncul tokoh-tokoh pendiri Kerajaan Palembang, termasuk Ki Gede Ing Suro.
- Grand Filano Hybrid 2026, Warna Baru Makin Kalcer & Stylish
- FES: Inisiatif Perempuan Kembalikan Pangan Lokal
- Arah Industri Pindar 2026 di Tengah Pengetatan Regulasi
Jika dibandingkan dengan bangunan bersejarah lain di Palembang, usia situs ini terpaut ratusan tahun lebih tua. Makam Kawah Tengkurep baru dibangun sekitar 1730-an, sementara Masjid Agung Palembang dan Benteng Kuto Besak berasal dari abad ke-18. Artinya, jauh sebelum bangunan-bangunan ikonik itu berdiri, bata-bata candi Ki Gede Ing Suro telah lebih dulu menyaksikan perubahan zaman di wilayah ini.
“Kalau dibandingkan, Kawah Tengkurep itu baru dibangun sekitar 1730-an, Benteng Kuto Besak juga abad ke-18. Jadi, secara usia, Ki Gede Ing Suro jauh lebih tua,” jelas Robby.
Sebagai pemimpin, Ki Gede Ing Suro memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Ketika raja memeluk Islam, masyarakat pun banyak yang mengikuti. Proses masuknya Islam tidak hanya berlangsung melalui dakwah, tetapi juga melalui keteladanan pemimpin dan hubungan sosial dengan penguasa.
Dari sekitar dua puluh makam yang ada di kompleks ini, hanya beberapa nama yang masih dapat dikenali, seperti Ki Gede Ing Suro Muda, Tan Pualang Cian Cang, dan Raden Kusumoningrat. Selebihnya, nisan kayu telah lapuk dimakan usia, membuat identitas para tokoh yang dimakamkan di sana perlahan menghilang. Yang tersisa kini hanyalah susunan bata dan tanda makam tanpa nama, menyimpan kisah yang belum sempat diceritakan kembali.
“Yang sudah kita ketahui itu Ki Gede Ing Suro Muda, lalu Tan Pualang Cian Cang, dan Raden Kusumoningrat. Untuk makam yang lain, makamnya sudah ada, tapi nama-namanya belum diketahui sampai sekarang,” ujar Darman, Juru Pelihara (jupel) Makam Ki Gede Ing Suro.
Keunikan utama situs ini terletak pada bentuknya yang masih berupa candi bata, bukan makam biasa. Bagian atas candi digali dan dijadikan tempat pemakaman. Bentuk ini menunjukkan kuatnya akulturasi budaya Hindu–Budha dan Islam, berbeda dengan makam lain di Palembang seperti Kawah Tengkurep yang berupa gundukan tanah dengan bangunan penutup. Model candinya pun mirip dengan situs-situs candi di Bumi Ayu dan Muaro Jambi yang khas Asia Tenggara.
Berdasarkan hasil ekskavasi arkeolog, struktur bangunan candi sebagian besar masih asli, baik dari bentuk persegi maupun susunan batanya. “Secara umum, struktur bangunannya masih asli, hanya beberapa bagian yang memang harus diganti dengan material serupa,” kata Robby.
Dahulu, di atas candi terdapat bangunan kayu seperti pendopo atau joglo. Namun, bangunan tersebut telah terbakar dan tidak tersisa. Situs ini kemudian kembali ditemukan oleh peneliti Belanda dan mengalami proses pembugaran sejak sekitar tahun 1970 hingga 1980-an.

Meski menyimpan lapisan sejarah yang panjang, kepedulian sebagian masyarakat sekitar terhadap situs ini masih tergolong rendah. Karena kompleks makam bersifat terbuka, perusakan kerap terjadi, salah satunya terlihat pada pagar besi di dalam pagar tembok yang rusak. Peziarah pun lebih banyak datang dari luar daerah, terutama dari Jawa atau keturunan transmigran.
Perawatan situs berada di bawah tanggung jawab Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VI Provinsi Sumsel. Warga sekitar ditunjuk sebagai juru pelihara melalui surat keputusan untuk membersihkan area, memotong rumput, dan menjaga kondisi bangunan. Dengan peralatan sederhana dan keterbatasan fasilitas, merekalah yang setiap hari menjaga agar situs berusia ratusan tahun ini tetap bertahan.
Kompleks makam ini terbuka selama 24 jam karena berada di dekat pemakaman umum warga. Tidak ada biaya resmi untuk berkunjung, biasanya pengunjung memberikan sedekah yang digunakan untuk perawatan. Tantangan lain datang dari faktor cuaca serta perilaku pengunjung yang belum memahami aturan pelestarian, seperti naik ke atas candi, duduk dan berdoa di atas struktur bata, atau menginjak bangunan dengan sepatu.
- Simak Ini Sebab Gen Z Enggan Menikah
- Hoaks: Video Menteri Purbaya Cairkan Kenaikan Gaji Pensiun
- Sinopsis Can This Love Be Translated, Romansa Lintas Bahasa
Darman berharap, ke depan situs ini dapat dirawat dengan lebih baik, dilengkapi fasilitas seperti tempat berteduh, air bersih, dan penerangan, sehingga bisa menjadi wisata religi dan sejarah yang layak serta bermanfaat bagi masyarakat.
Usulkan Nama Percandian Diperjelas
Sementara itu, Robby Sunata berharap agar situs ini dilengkapi atap pelindung tanpa menutup sisi kanan dan kiri, sehingga bangunan tetap terlihat sekaligus terlindung dari hujan dan panas. Ia juga mengusulkan agar nama situs diperjelas menjadi “Percandian Kompleks Makam Ki Gede Ing Suro”, agar masyarakat memahami bahwa tempat ini bukan sekadar makam, melainkan juga situs candi.
Melalui kegiatan edukasi, komunitas cagar budaya terus berupaya memperkenalkan situs ini kepada masyarakat, baik melalui konten sejarah di grup WhatsApp maupun dengan mengajak warga datang langsung ke lokasi untuk memahami fungsi dan makna bangunan yang telah bertahan sejak berabad-abad lalu.
Di tengah sunyi kompleks makam yang terbuka sepanjang hari, harapan itu terus dijaga oleh warga sekitar dan penggiat sejarah agar bangunan bata yang telah bertahan ratusan tahun ini tidak hanya menjadi saksi masa lalu, tetapi juga bagian dari masa depan Palembang. (Ani Mustika Wati).