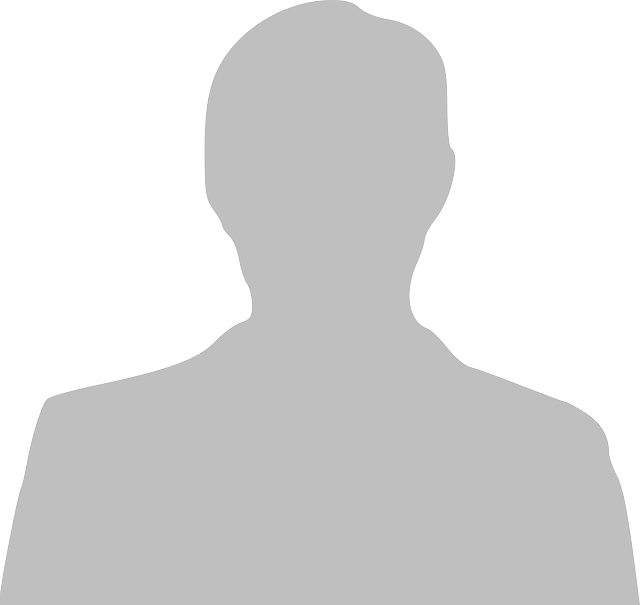Ragam
Konferensi ICIR: Jangan Mudah Terjebak Ujaran Kebencian
SOLO, WongKito.co – Pembicara pada International Conference and Consolidation on Indigenous Religions (ICIR) mengimbau jangan mudah terjebak dalam narasi politik ujaran kebencian.
"Kita tidak ingin mengulang kejadian di tahun 2014,” kata Herlambang P. Wiratraman, ahli dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan Konferensi ICIR hari kedua di Universitas Sebelas Maret Solo, Kamis (23/11/2023).
Sesi panel tersebut mengambil topik “Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam KUHP yang Baru”.
Dalam paparannya, Herlambang mengungkapkan kebebasan berekspresi adalah salah satu yang paling terdampak dari konteks politik hukum manipulatif yang dominan akhir-akhir ini.
Baca Juga:
- Asupan Makanan dan Pola Perawatan Mempengaruhi Kesehatan Rambut
- OPEC+ Akan Bertemu Besok Membahas Kebijakan Bersama
- Jangan Lupa! Yuk Kunjungi Pameran Benda Purba di OPI Mal, Saksikan Beragam Keajaiban Dunia asal Sumsel
Ia menambahkan, KUHP membuka ruang untuk potensi manipulasi yang lebih sistematis.
Sementara itu, Iqbal Ahnaf, dosen pascasarjana di Program Studi Agama dan Lintas Budaya atau CRCS Universitas Gadjah Mada, menunjukkan data bahwa ada 72 kasus terkait KUHP dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2021.
Kasus-kasus tersebut terdiri dari 61 kasus penghinaan terhadap kekuasaan dan 11 lainnya merupakan kasus ujaran kebencian terkait identitas, katanya.
Terkait dengan hal itu, Johana Poerba dari Institute for Criminal Justice Reform menegaskan bahwa
“Penting untuk membedakan apa yang termasuk ekspresi kritik terhadap status quo kekuasaan dan apa yang termasuk hasutan kebencian,” katanya.
Ia mempertanyakan, bagaimana pasal ujaran kebencian yang tujuannya melindungi kelompok rentan, justru menimbulkan pembatasan-pembatasan hak mereka.
Salah satu poin penting yang juga dibahas dalam sesi ini adalah terkait dengan media sosial yang sering menjadi ruang terjadinya pelanggaran kebebasan berekspresi dan hasutan kebencian.
Leonard C. Epafras, dosen pascasarjana di Indonesian Consortium for Religious Studies atau ICRS Universitas Gadjah Mada, menyayangkan bahwa saat ini media sosial justru memberi rewards pada orang-orang yang menimbulkan konflik dan keramaian.
Merespons pertanyaan salah satu peserta terkait dengan algoritma media sosial, ia menjelaskan bahwa algoritma itu sebenarnya biasa saja, tetapi ia di-framing menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Walaupun juga memang ia sering dimanfaatkan.
Berkesinambungan dengan pembahasan ini, panel selanjutnya mengangkat topik “Pelanggaran terkait Agama atau Keyakinan dalam KUHP yang Baru: Melindungi Siapa?” dengan dimoderatori oleh Samsul Maarif, Direktur Program Program Studi Agama dan Lintas Budaya atau CRCS Universitas Gadjah Mada.
Pembicara dalam sesi ini adalah Uli Parulian Sihombing dari Komnas HAM yang hadir secara daring, Asfinawati dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, dan Zainal Bagir dari Indonesian Consortium for Religious Studies atau ICRS Universitas Gadjah Mada yang hadir secara langsung.
Uli menegaskan bahwa “Komnas HAM merekomendasikan pendekatan keadilan mediasi penal dalam penanganan kasus-kasus penodaan agama/kepercayaan.”
Dasarnya adalah “keadilan restoratif yang menekankan pada upaya pemulihan, dimana korban dan pelaku dengan difasilitasi oleh APH mencari solusi untuk upaya-upaya pemulihan.” Menariknya, ia menyebutkan bahwa konsep ini sebenarnya berakar pada hukum-hukum adat kita, yang kemudian diambil oleh sarjana barat dan disebut sebagai keadilan restoratif.
Baca juga:
- Gerakan Masyarakat Sipil #BersihkanIndonesia Ungkap 7 Masalah Substansi Dokumen CIPP JETP 2023
- Simak inilah, 5 Furniture Murah tapi Kesannya Mewah
- Bank Raksasa AS: Citigroup PHK Massal Karyawan
Melanjutkan pembahasan ini, Asfinawati mengatakan bahwa sulit untuk bisa membayangkan apa makna dari kekerasan terhadap agama.
“Agama tidak mungkin jalan sendiri ke kantor polisi”, ungkapnya.
Dalam pandangannya, Asfin melihat bahwa penodaan agama tidak ada gunanya. Ia mengatakan jika itu diharapkan membawa pada keadilan dan perdamaian, itu tidak mungkin terjadi. Kenyataannya itu menimbulkanperselisihan antara kelompok yang berbeda keyakinan.”
Ia juga melihat ada bias dalam peraturan ini sebab yang diatur hanya hasutan agar orang tidak beragama atau berkepercayaan, tidak ada untuk sebaliknya yaitu hasutan untuk beragama atau berkepercayaan.
“Siapa yang menentukan telah ada pernyataan kebencian terhadap agama adalah kelompok mainstream,” tegas Asfin.
Selain itu, Asfinawati juga menunjukkan data bahwa ada “laporan kelompok penghayat, 6 kelompok non agama, dari anggota aliran yang dianggap sesat tidak ditindaklanjuti atau terhadap kelompok mayoritas keagamaan tidak ditindaklanjuti.”
Pada akhirnya, Asfinawati mengusulkan agar upaya yang dilakukan ke depan adalah untuk memenangkan ruang pemaknaan hukum-hukum yang sudah disahkan ini.
“Sekalipun hukum memang tekah diciptakan, ruang pemaknaannya bisa kita rebut untuk kelompok minoritas, baik melalui jalan konstitusi, politik, maupun komisi independen,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa regulasi penodaan agama sebenarnya tidak ada gunanya. Ia mengatakan “jika itu diharapkan membawa pada keadilan dan perdamaian, itu tidak mungkin terjadi. Kenyataannya itu menimbulkan perselisihan antara kelompok yang berbeda keyakinan.”
Hal serupa juga disampaikan oleh Zainal Abidin Bagir dari ICRS UGM. Zainal mengingatkan pentingnya tidak menggunakan istilah penodaan agama lagi, karena sudah tidak ada dalam realitas litigasinya (KUHP).
“Meski masih ada beberapa masalah serius dalam pasal-pasal terkait agama, ada juga beberapa titik masuk baru untuk perbaikan. Namun juga, seberapa baiknya hukum yang baru pun, tidak ada jaminan praktik akan berubah”, kata Zainal.
Baca Juga:
- Doyan Makan Hati Ayam, Yuk Bikin Sambal Ati Ampela tapi Cek dulu Kandungan Nutrisinya
- Nikmati Kopi Hitam, di Kedai Nan Yo Padang, Nuansa Tempo Dulu Bikin Betah Ngopi
- Pertamina Wujudkan Sekolah Energi Berdikari di Palembang
Sejalan dengan ide keadilan restoratif yang disampaikan Uli sebelumnya, Zainal juga sepakat bahwa pemidanaan sebaiknya dihindari, termasuk bagi orang-orang yang dianggap intoleran sekalipun.
“Memang akan selalu ada orang intoleran, tapi tempatnya bukan di penjara. Pidana bukan jalan terbaik, dan sebisa-bisanya dihindari,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Zainal mengatakan, “kita ambil saja ini (disahkannya KUHP) sebagai momentum untuk mengangkat kembali isu penodaan agama yang beberapa tahun lalu telah diputuskan oleh MK untuk direvisi, tetapi sampai sekarang belum dilakukan.(ril)