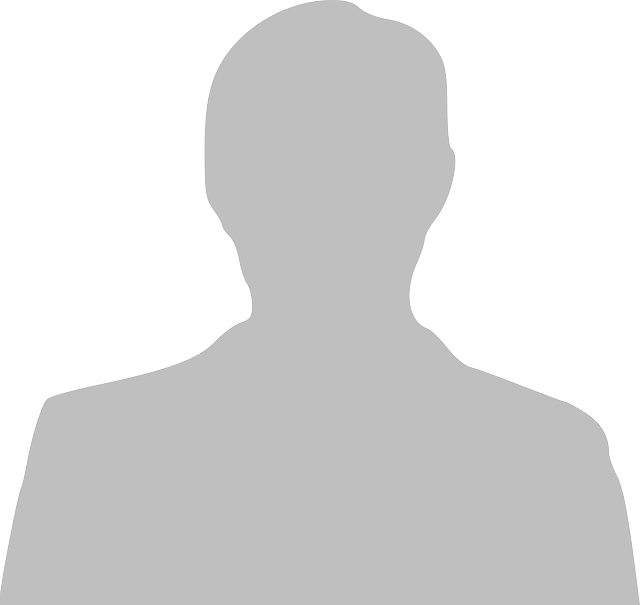YundaKito
Mengenal Marsinah, Aktivis Buruh Perempuan yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
JAKARTA, WongKito.co – Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, antara lain seorang aktivis buruh perempuan dari Nganjuk, Jawa Timur, Presiden ke-4 Indonesia, dan Presiden ke-2 Indonesia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai 40 calon pahlawan yang diajukan oleh Kemensos telah memenuhi kriteria dan pantas dimasukkan ke dalam daftar. Di antara 40 nama tersebut terdapat Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dan Marsinah, yang dikenal sebagai seorang aktivis buruh.
“Kalau kelayakan, semuanya sudah layak, tetapi keterbatasan itu diserahkan nanti kepada Presiden atas rekomendasi dari Dewan Gelar,” ujar Fadli di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Proses pengusulan nama pahlawan nasional dimulai dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, setelah pembahasan di tingkat daerah dan ditanda tangani bupati atau wali kota, dokumen tersebut diteruskan ke gubernur sebelum akhirnya diterima oleh Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian lebih lanjut.
Lantas, Siapa Marsinah?
Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia tumbuh bersama dua saudara perempuannya setelah ibunya meninggal ketika Marsinah berusia tiga tahun. Hal tersebut membentuknya menjadi pribadi yang penuh motivasi tinggi dan pantang menyerah.
- Harga Emas Turun Rp17 ribu Pergram di Galeri 24 Palembang, Cek Rinciannya
- Yuk Buat Kripik Brownies yang Enak
- Hoaks: Tautan Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA hingga S2, Cek Faktanya Yuk!
Marsinah dikenal sebagai sosok yang cerdas, sering menempati peringkat pertama di kelasnya. Namun, ia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya.
Pada 1989, Marsinah merantau ke Surabaya untuk bekerja di pabrik plastik SKW di Kawasan Industri Rungkut. Karena penghasilannya masih kurang, ia menambah pendapatan dengan berjualan nasi bungkus keliling.
Marsinah juga sempat bekerja di perusahaan pengemasan barang sebelum pindah ke Sidoarjo pada 1990 untuk bekerja di PT CPS. Selama di PT CPS, ia dikenal vokal dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan rekan-rekannya serta aktif dalam kegiatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di unit kerja PT CPS.
Pada saat itu, SPSI menjadi satu-satunya organisasi buruh di Indonesia karena pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan wadah tunggal organisasi, yang berarti setiap profesi atau pekerja hanya diizinkan memiliki satu organisasi.
Pada pertengahan Maret 1993, Gubernur Jawa Timur Soelarso, mengeluarkan surat edaran yang mengimbau seluruh pengusaha di Jawa Timur untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Surat edaran itu memicu sejumlah buruh untuk menuntut realisasi, bahkan banyak yang melakukan mogok kerja.
Marsinah menjadi salah satu buruh yang vokal dalam memperjuangkan tuntutan di tempat kerjanya, termasuk memimpin penolakan terhadap perusahaan yang meminta buruh kembali bekerja saat mogok. Ia juga termasuk dalam 15 perwakilan buruh yang berunding dengan perusahaan dan Departemen Tenaga Kerja di Sidoarjo.
Karena kebuntuan negosiasi pada 3 dan 4 Mei 1993, seluruh karyawan PT CPS melakukan mogok dan menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Kenaikan ini sesuai dengan Keputusan Menteri No. 50/1992 yang menetapkan upah minimum regional di Jawa Timur saat itu.
Di bawah rezim militeristik yang dipimpin Soeharto pada masa Orde Baru, pemerintah memastikan adanya dasar hukum untuk mengawasi dan mengatur aksi protes buruh, antara lain melalui Surat Keputusan Bakorstanas No.02/Satnas/XII/1990 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 342/Men/1986.
Di situ tertulis jika terjadi perselisihan antara buruh dan pengusaha, militer memiliki hak untuk bertindak sebagai mediator atau penengah. Mereka inilah yang kemudian dihadapi oleh Marsinah dan rekan-rekan buruh saat melakukan mogok dan menggelar protes.
Tragedi tragis yang menimpa Marsinah bermula dari unjuk rasa dan mogok kerja yang ia lakukan bersama rekan-rekannya pada 3-4 Mei 1993, di mana mereka mengajukan 12 tuntutan.
Sayangnya, setelah unjuk rasa tersebut, Marsinah dan rekan-rekannya dipanggil oleh Kodim 0816 Sidoarjo. Mereka dituduh menggunakan cara PKI/Komunis. Pada 5 Mei 1993, Marsinah menghilang setelah mengunjungi rumah rekannya.
Pada 8 Mei 1993, sekelompok anak-anak menemukan jasadnya dalam kondisi mengenaskan. Diduga Marsinah dianiaya, karena tubuhnya penuh luka dan kaku membiru saat ditemukan. Hingga kini, belum ada kejelasan yang mengungkap pelaku atau alasan di balik kejadian tersebut.
- Warga Sako Padati Pasar Murah, Minyak Goreng hingga Beras Dijual Lebih Murah dan Dapat Kupon Rp10 Ribu
- Balai Karantina Palembang Gelar Vaksinasi Gratis, Simak Ciri Hewan Terjangkit Rabies
- Beras Murah, Sepeda Tua, dan Rasa Syukur di Pasar Murah Sako Palembang
Media massa pada saat itu baru mulai menyoroti kasus ini sekitar sebulan setelah peristiwa, akibat desakan dari mahasiswa, buruh, dan lembaga swadaya masyarakat yang prihatin atas pembunuhan tersebut.
Kasus ini kemudian menjadi simbol penting dalam perjuangan hak-hak buruh dan isu kondisi kerja di Indonesia.
Kisah Marsinah, aktivis buruh muda yang dibunuh secara keji pada masa Orde Baru adalah sebuah gambaran mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dan juga sempat mendunia.
Tulisan ini telah tayang di TrenAsia.com, jejaring media WongKito.co, pada 22 Oktober 2025.