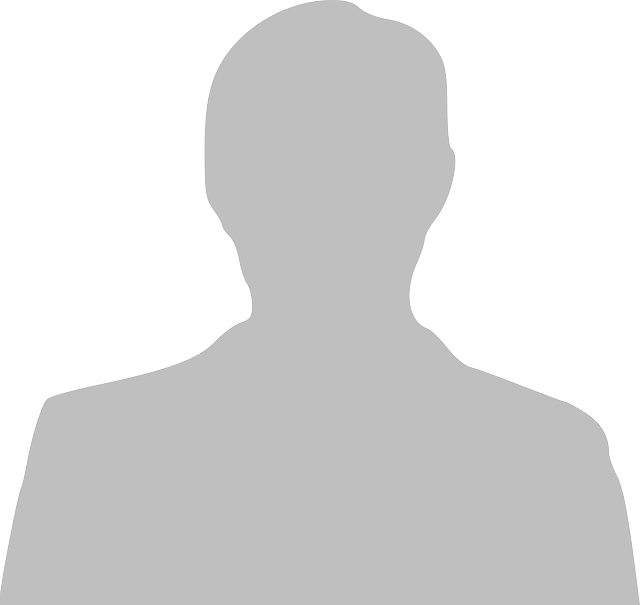BucuKito
Pergeseran Nafas Hidup Warga Desa Sedupi, Ketika Sungai Lematang tak Bebas bagi Nelayan
EMBUN pagi masih menempel di dedaunan ketika saya menginjak tanah Desa Sedupi, Senin (17/11/25). Udara dingin bercampur aroma kayu basah menemani langkah menuju rumah kayu Sumhilal.
Di desa yang tenang itu, perubahan hidup warga terasa mengalir pelan seperti Sungai Lematang yang tak lagi sekeruh dulu, tapi juga tidak lagi segembira masa lampau.
Di rumah kayu yang tetap kokoh meskipun dimakan usia, Sumhilal (74) duduk sambil menatap ke luar jendela. Garis wajahnya menyimpan banyak cerita. “Aku nih dari tahun 1971 nyari ikan,” ucapnya sambil tersenyum kecil, seolah kembali pada masa ketika sungai menjadi sahabat paling setia. Tapi kini, senyumnya lebih banyak menyimpan rindu.
“Dulu banyak, sekarang dak banyak lagi. Susah. Seminggu itu paling sekali dapat, kadang idak samo sekali,” katanya.

Baca Juga:
- Simak 5 Cara Mencegah Ular Masuk Rumah Saat Musim Hujan
- Cek Yuk 5 HP Murah Rp1 Jutaan di Akhir 2025, Ada Redmi A5!
- PB PMII: Berhenti Bermain Retorika, Ayo Tetapkan Darurat Nasional untuk Bencana Sumatera
Dikuasai Pemerintah
Perubahan lingkungan dan sistem lelang wilayah tangkap membuat kebebasan mereka hilang perlahan. Lebung tempat anak-anak muda dulu belajar menebar jala, kini dikuasai kelompok tertentu.
“Kalau tidak ikut lelang, tidak bisa cari ikan. Dak bebas lagi,” ujar Sumhilal.
Sungai Lematang masih mengalir, tetapi tidak lagi menjadi penopang utama hidupnya.
Tak jauh dari sana, rumah panggung milik Badar (73) berdiri menghadap sungai yang sama. Dari teras, ia menatap air yang mengalir tenang air yang dulu ia kenal, yang sekarang terasa asing bagi seorang mantan nelayan.
“Dulu aku muda masih nelayan. Sekarang tidak mampu lagi,” katanya. Suaranya datar, seperti sudah lama berdamai dengan keputusan untuk meninggalkan sungai. Kini, ia lebih banyak menghabiskan waktu di sawah bersama anaknya.
“Petani itu lebih bagus. Tulang punggung negara itu kan petani,” katanya sambil tertawa, mencoba meneguhkan keyakinan yang perlahan tumbuh bersama padi-padi kecil di tanahnya.

Sawah kecil itu tidak menghasilkan banyak, tetapi cukup untuk makan. “Kalau ada sawah, dak perlu banyak beli beras,” tambahnya. Ada ketenangan baru yang ia temukan di tanah, meski bukan itu yang dulu ia impikan ketika muda.
Peralihan pekerjaan dari nelayan ke petani bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Bantuan pemerintah lebih banyak mengalir untuk pertanian, sementara alat tangkap ikan tak pernah sampai ke tangan mereka.
“Ikan itu susah didapat sekarang. Kadang beli secukupnya untuk dikonsumsi,” kata Badar lirih kalimat yang mencerminkan betapa jauhnya perubahan yang mereka rasakan.

Meski begitu, baik Sumhilal maupun Badar menyimpan rindu yang sama. Mereka merindukan masa ketika fajar selalu membawa harapan baru dari sungai.
“Kalau dulu, pagi tu ada ikan. Tidak susah,” kata Sumhilal, kali ini tanpa tawa.
Baca Juga:
- Kompleks Pemakaman Sabokingking: Saksi Sejarah, Awal Massa Kesultanan Palembang Darussalam
- Pemprov Sumsel Luncurkan Website Cek Fakta
- Kampanye 16 HAKTP: FJPI Sumsel Ajak Jurnalis Pahami KBGO hingga Teknik Penulisan Etis
Di Desa Sedupi, cerita mereka bukan satu-satunya. Di balik setiap rumah panggung, ada kisah tentang warga tua yang perlahan meninggalkan sungai yang membesarkan mereka. Ada babak hidup yang berubah, ada harapan yang berpindah dari aliran air ke gumpalan tanah sawah.
Sungai mungkin tak lagi menghidupi seperti dulu, tetapi warga Sedupi terus bertahan. Dengan tangan yang semakin renta, mereka menanam kembali harapan kali ini di tanah yang mereka pijak, bukan di air yang tak lagi bisa mereka prediksi.(Mg/Kgs Muhammad Haikal Muharam)