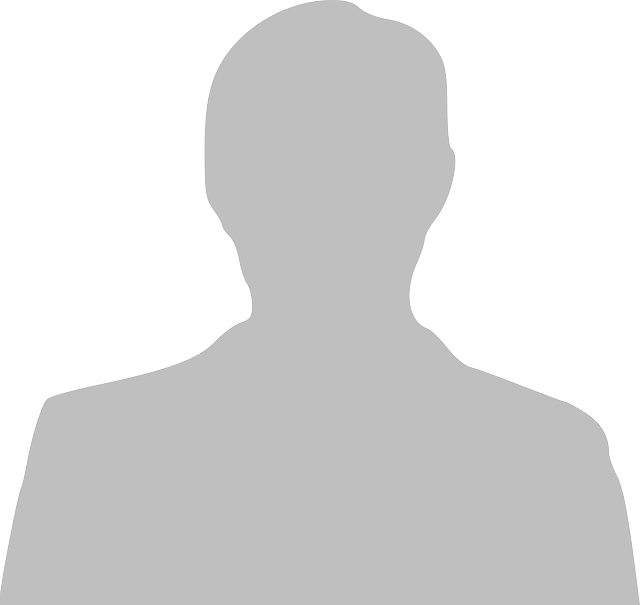KabarKito
Sejarawan: Banyak Sungai Ditimbun, Wajah Lama Palembang Nyaris Hilang
PALEMBANG, WongKito.co - Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, sungai-sungai di kota Palembang Palembang yang dulu menjadi nadi kehidupan kota kini menghilang akibat ditimbun.
Pemerintah Belanda mencatat ratusan anak sungai di Kota Palembang, sebagian besar telah ditimbun, tercemar limbah, atau dibiarkan mati.
Ironisnya, pemerintah justru mengabaikan akar masalahnya, sementara masyarakat kehilangan kesadaran akan pentingnya ekosistem sungai.
Sejarawan Universitas Sriwijaya (Unsri) yang juga Ketua Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan (Puskass), Dr. Dedi Irwanto, M.A., mengatakan pentingnya penyelamatan sungai –sungai di kota Pempek.
"Palembang adalah kota sungai. Bukan hanya karena Sungai Musi, tetapi juga karena seluruh nadi kehidupan masyarakatnya dahulu mengalir lewat ratusan anak-anak sungai," kata Dedi saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sungai: Jejak Sejarah, Realita Hari Ini, dan Masa Depan Kota Palembang", Senin (14/7/2025).
Baca Juga:
- Prakiraan Cuaca Palembang Hari Ini: Rabu 16 Juli 2025, Hujan Ringan
- Begini Resep Pisang Berendam Fla Creamy
- Simak Cara Membedakan Beras Asli dan Oplosan
Di tepian sungai-sungai tersebut, menurut Dedi, dulunya tumbuh pasar, rumah, hingga pusat kekuasaan.
"Namun kini, wajah lama kota ini nyaris tak dikenali lagi. Banyak sungai yang ditimbun, dialihkan, disempitkan, bahkan dibiarkan mati. Palembang, yang dikenal sebagai kota air, kini kehilangan sungainya," katanya.
Dia menjelaskan bahwa Palembang pernah memiliki budaya tepian sungai yang kuat dimana rumah-rumah menghadap ke sungai, dan sungai menjadi jalur utama untuk transportasi, perdagangan, serta pemerintahan.
Namun, sayangnya, budaya tersebut kini hampir hilang dari kesadaran masyarakat. Modernisasi telah mengubah cara pandang kita terhadap sungai. Dari ruang hidup, menjadi sekadar saluran buangan, ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejak awal abad ke-20, kolonialisme membawa perubahan besar. Sungai dianggap sebagai masalah sanitasi yang harus ditaklukkan.
Pemerintah Belanda mulai menimbun dan membangun jalan di atas sungai. Pada tahun 1913, tapi Pemerintah Gemeente Palembang mengundang ahli sungai dari Belanda, Rudolf A. van Sandick, untuk meneliti sistem perairan kota.
Kemudian, Ia membagi anak sungai menjadi dua kategori yang alami dan buatan. Namun, alih-alih memperkuat sistem air tersebut justru menutup banyak sungai demi pembangunan pelabuhan, pasar, dan jalan, katanya.
Dedi mengungkapkan salah contohnyaa adalah Sungai Tengkuruk. Pada abad ke-17, sungai ini menjadi jalur diplomatik menuju Keraton Cinde Belang. Kini, tak ada lagi jejak air di sana, hanya tersisa pasar, beton, dan kemacetan jalan kota.
"Banyak warga tidak tahu bahwa jalan yang mereka lewati setiap hari dulunya adalah sungai," kata dia.
Ia menekankan bahwa perubahan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan membentuk ruang.
Di satu sisi, kolonialisme membawa zonasi dan pembangunan, tetapi di sisi lain, juga menghapus sistem ruang lokal yang berbasis air dan telah ada selama ratusan tahun.
Transformasi Palembang terus berlanjut hingga era Republik. Proyek perluasan kota, pengeringan lahan, dan urbanisasi semakin mempercepat hilangnya anak sungai.
Dari 117 anak sungai yang tercatat pada awal abad ke-20, kini sebagian besar hanya tinggal nama. Banyak yang berubah menjadi got tertutup, sementara sisanya mati perlahan sebagai saluran limbah, katanya.
Menurut dia, revitalisasi seperti proyek Sekanak Lambidaro memang memberikan secercah harapan. Namun, menurut Dedi, jika tidak disertai kesadaran sejarah dan budaya, proyek-proyek semacam itu hanya akan menjadi lanskap tanpa jiwa.
"Kota yang menutup airnya sendiri harus belajar membuka kembali, bukan hanya jalur airnya, tetapi juga memori kolektifnya," tegasnya.
Dedi menekankan bahwa membangun kota berkelanjutan di atas lahan bekas rawa bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang rekonsiliasi ruang dan kesadaran sejarah.
Palembang, dan kota-kota sungai lainnya di Indonesia, perlu menata ulang narasi kotanya dari yang meminggirkan sungai menjadi kota yang merangkul dan memulihkannya. Dalam konteks krisis iklim dan tata ruang hari ini, menyelamatkan sungai bukan soal nostalgia, tetapi keharusan ekologis dan kebudayaan. Karena ketika sungai hilang, yang ikut tenggelam bukan hanya air, tetapi juga identitas kota itu sendiri, katanya.
Revitalisasi Sungai
Hal senada dikemukakan Sejarawan dari UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Kemas A.R. Panji, M.Si., juga menegaskan pentingnya penyelamatan anak-anak Sungai Musi di kota Palembang.
"Sungai Musi masih berkilau, tetapi kilau itu bukan lagi cermin kejernihan. Di balik alirannya, ada cerita-cerita lama yang nyaris tenggelam bersama lumpur dan limbah yang lebih menyengat dari harapan," katanya.
Menurutnya, Palembang bukan kota biasa. Ia lahir dari air. Sungai Musi dan ratusan anak sungainya tidak hanya menjadi jalur lalu lintas, tetapi juga ruang hidup yang membentuk lanskap budaya, sosial, dan ekonomi sejak abad ke-7.
"Palembang itu peradaban air .Kita bukan hanya kota di tepian sungai, melainkan kota yang tumbuh di atas sungai," ujar dia.
Dan dari catatan I-Tsing pada abad ke-7 hingga peta kolonial Belanda pada abad ke-19 dan 20, menurutnya tercatat ada lebih dari 700 sungai yang mengaliri kota ini.
Namun kini, menurut data Koalisi Kawali (2025), hanya tersisa 114 sungai aktif. Ini adalah alarm keras akan abainya pengelolaan warisan ekologis Palembang.
Tepi-tepi sungai yang dulu hidup dengan rumah panggung dan perahu rakit kini berubah menjadi kanal mati dan drainase beton. Sungai Sekanak, yang dulunya menghubungkan komunitas kampung tradisional, kini tengah direstorasi lewat proyek "Sekanak Lambidaro Riverfront".
Proyek ini diharapkan menjadi titik balik meski tak sedikit warga yang pesimis jika tak disertai edukasi dan partisipasi masyarakat. "Restorasi tanpa partisipasi warga hanya akan jadi proyek mercusuar," katanya.
Apalagi menurutnya, pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, sungai adalah jalur perdagangan, sistem pertahanan, sekaligus tempat tumbuhnya budaya rakyat. Benteng Kuto Besak, misalnya, dibangun di antara empat sungai: Kapuran, Sekanak, Tengkuruk, dan Musi. Dari sungai-sungai inilah lahir syair lisan, pantun, hingga upacara adat.
"Sekarang, anak-anak kita banyak yang tak kenal lagi nama-nama sungai di kampungnya. Sungai Aur, Prigi, atau Sekanak terdengar asing. Padahal itu identitas,” katanya prihatin.
Menurut Kemas, inilah paradoks Palembang, kaya akan sejarah sungai, namun miskin pengelolaan.
"Urbanisasi yang tak terarah menjadikan sungai sebagai korban. Pencemaran, pendangkalan, hingga pembangunan di sempadan sungai menjadi pemandangan sehari-hari," katanya.
Baca Juga:
- Hoaks: Suhu Juli-Agustus 2025 Lebih Dingin karena Aphelion, Cek Faktanya!
- Bantu Benih Ikan, Dukung Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
- Cegah Sunat Perempuan, Penyusunan Modul Edukasi Dimulai
Namun, ia percaya harapan belum musnah. Penelitian menunjukkan bahwa sungai masih bisa menjadi koridor wisata sejarah dan ekonomi hijau.
Dimana rumah-rumah tua seperti Rumah Limas Cek Mas dan rumah Baba Ong Boen Tjit adalah saksi bisu masa kejayaan perdagangan sungai yang kini berpotensi menjadi destinasi wisata sejarah.
"Revitalisasi anak sungai, pemberdayaan komunitas tepian, promosi perahu ketek, dan pelestarian rumah limas adalah strategi yang kami ajukan," katanya.
"Jika kita gagal menjaga sungai hari ini, maka kita sedang menenggelamkan peradaban esok hari," katanya.
Ia menegaskan penyelamatan sungai bukan soal nostalgia, melainkan soal masa depan. Palembang memiliki banyak regulasi dari UU Sumber Daya Air, Perda, hingga Perwali—tetapi hukum tanpa penegakan hanyalah lembaran kertas.
"Yang kita butuhkan sekarang adalah kesadaran kolektif. Menjaga sungai berarti menjaga sejarah, menjaga lingkungan, dan menjaga masa depan," katanya.(ril)