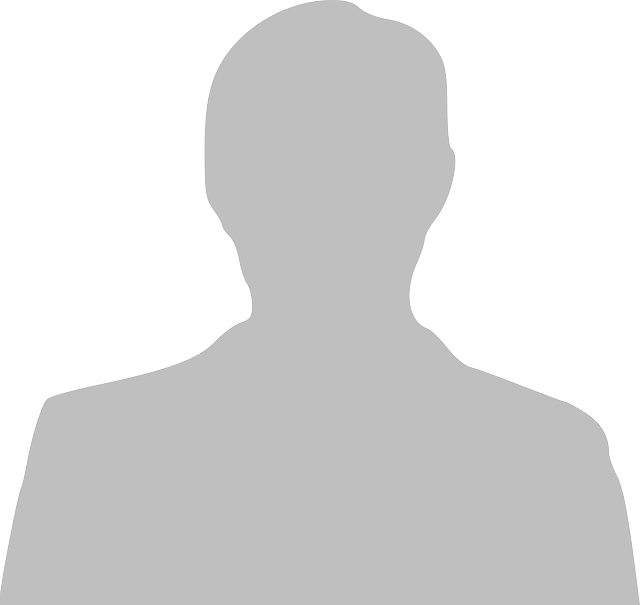BucuKito
Suara Sunyi dari Balik Debu Batu Bara
Oleh: Joka Munir*
Kami berangkat dari Palembang ke Lahat naik kereta api. Dari balik jendela kereta, sawah dan pepohonan berganti-ganti, seolah ikut berlari bersama cepatnya kereta.
Sesampainya di Lahat, kami disambut dengan hawa panas yang menyergap. Teriknya matahari bercampur dengan panas mesin kereta yang belum benar-benar padam. Rasanya seperti berdiri di antara dua api, panasnya bukan cuma di kulit, tapi sampai ke kepala. Aku cuma bisa tertawa kecil, sambil menyeka keringat, berfikir betapa anehnya rasa lelah dan kagum bisa datang bersamaan.
Setelah turun dari kereta, kami berjalan ke arah tempat tunggu di stasiun. Aku duduk di kursi yang terbuat dari besi. Walaupun tempatnya cukup teduh, tetapi hawa panas tetap saja tidak bisa terbendung, udara seperti terjebak di bawah langit yang membara, membuat napas terasa berat. Jemputan belum juga datang. Sambil menunggu, aku mengobrol dengan temanku, Fathul.
“Panasnya kayak menggigit kulit, ya,” ujarku berharap sedikit angin datang dari arah mana pun.
“Iya, kayak dibakar pelan-pelan,” kata Fathul sambil menyipitkan mata ke arah cahaya.
Kami tertawa kecil di tengah terik yang seakan tak mau beranjak.
Waktu berjalan pelan, sampai akhirnya jemputan datang. Mobil itu berhenti tidak jauh dari tempat kami duduk. Debu di sekitar stasiun ikut berterbangan tertiup angin yang panas. Kami segera berdiri mendekati mobil dengan membawa barang bawaan.
Begitu hendak memasukkan barang ke bagasi, panas matahari langsung terasa benar-benar menggigit kulit. Sinar matahari memantul di kap mobil, silau membuat mata nyaris tak bisa terbuka. Rasanya seperti disorot cahaya panggung yang terlalu dekat.
“Behhh, panasnyaaa!” seruku dengan suara agak keras sambil mengangkat tas ke bagasi.
“Iya lagiii!” sahut Miftah dan Fathul kompak.
Setelah semua barang dimasukan ke dalam bagasi, kami langsung berangkat. Di dalam mobil ada aku, Fathul, dan Haikal. Begitu mobil melaju, udara dari pendingin mobil terasa seperti penyelamat setelah panas yang tadi membakar kulit.
Perjalanan terasa lebih tenang. Dari jendela mobil, pemandangan berganti perlahan antara pepohonan dan langit biru yang mulai tampak jernih. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat Gunung Jempol berdiri megah, seolah menyapa kami yang baru datang.
“Fathul, lihat gunungnya!” seruku sambil menunjuk ke arah luar jendela.
“Iya, bagus, ya. Itu juga kayak Bukit Barisan,” jawab Fathul sambil menatap kagum.
Haikal hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Setiap libur semester, ia selalu melewati daerah ini. Tentu tidak bagi kami, semuanya terasa baru dan menakjubkan. Mobil terus melaju meninggalkan stasiun dan panas yang terasa kejam, berganti dengan udara sejuk dan pemandangan yang menenangkan mata.
Setelah menempuh perjalan yang cukup jauh dan melewati jalan dengan banyak lubang, akhirnya mobil berhenti di sebuah rumah makan padang. Begitu kami turun, hawa panas yang sempat hilang kini terasa lagi, bahkan lebih menyengat dari yang kami rasakan di stasiun tadi.

Udara bercampur debu membuat kami refleks menutup hidung. Panasnya menempel di kulit, sementara aroma masakan dapur rumah makan menambah suasana ramai.
Sementara itu, Mbak Nila Ertina, Pemimpin Redaksi wongkito.co sekaligus dosen pembimbing kami, sedang memesan makanan di dalam. Waktu terasa berjalan lambat. Keringat mulai menetes. Kami saling pandang dengan ekspresi lelah.
“Kita tunggu di mobil saja, yuk. Panas di luar,” kataku.
Fathul dan Haikal mengangguk setuju. Kami pun kembali masuk ke mobil, menyalakan AC, dan menunggu di dalam sambil berharap makanan selesai dipesan.
Tak lama kemudian, Mba Nila keluar dari rumah makan sambil membawa beberapa bungkus makanan. Aroma masakan padang langsung menyeruak, membuat perut kami yang sejak tadi kosong ikut bergejolak. “Sudah dipesan semua,” katanya sambil tersenyum.
Kami segera membantu memasukan makanan ke dalam mobil, memastikan semuanya tersusun rapi agar tidak berantakan. Setelah semuanya beres, kami kembali berangkat menuju tempat tujuan. Mesin mobil menyala, roda kembali berputar di atas jalan yang panjang. Di dalam mobil, suasana terasa lebih tenang. Kami duduk diam beberapa saat, menikmati angin dari AC yang menyejukkan sambil menatap pemandangan yang perlahan berganti di luar jendela.
Setelah cukup lama di perjalanan, kami sampai di tempat tujuan yakni Posko Yayasan Anak Padi. Begitu mobil berhenti di depan halaman, beberapa orang langsung menyambut kami dengan senyum hangat. Rasa lelah di perjalanan seolah hilang begitu saja, tergantikan oleh suasana ramah dan penuh keakraban.
Kami segera menurunkan semua barang dan makanan yang tadi sempat dipesan di rumah makan padang. Tas, koper, dan bungkus makanan dibawa masuk ke dalam. Meski tubuh masih terasa lengket karena perjalanan panjang, semangat kami justru kembali naik.
- Hadirkan Promo Menarik, Tingkat Penghunian Kamar di Wyndham Opi Hotel Palembang Diatas 72 Persen
- Yuk Buat Kue Balok Lumer Matcha
- Harga Emas Antam Menguat Lagi, Berikut Rinciannya
Setelah semua barang masuk dan kami sempat membersihkan diri, suasana mulai berubah jadi lebih santai. Makanan dibuka, aromanya langsung memenuhi ruangan. Kami duduk bersama teman yang lain dan juga pengurus Yayasan Anak padi, makan sambil berbincang ringan.
Suasana hangat terasa di antara tawa dan percakapan kecil sore itu. Sederhana tapi meninggalkan kesan yang dalam. Setelah makan, kami mengobrol bersama pengurus Yayasan Anak Padi dan teman-teman yang lain.
Hingga tiba waktunya kami melanjutkan perjalanan menuju Sekolah Gajah. Karena mobil sudah penuh, aku dan Haikal memutuskan untuk yang membawa motor. Udara siang itu terasa menyengat dan jalanan berdebu menambah rasa lelah di antara panas yang terus menekan. Angin yang menerpa wajah bukan memberi sejuk, tapi justru membawa debu yang menempel di kulit. Aku separuh menunduk, mencoba menghindari silau matahari.
“Tahu gitu, tadi aku pakai masker dan helm, Kal,” ujarku sambil menyipitkan mata, berusaha menahan panas.
“Iya,” jawab haikal sambil ketawa kecil, “Tahu gitu bawa helm tadi.”
Kami berdua tertawa meski keringat sudah membasahi baju. Panasnya luar biasa, tapi entah kenapa suasana tetap menyenangkan, mungkin karena perjalanan ini bukan sekedar tentang jarak, tapi juga cerita yang kami jalani bersama.
Tidak lama setelah berangkat, kami berdua mulai memasuki jalan yang naik turun. Itu pertama kalinya aku menyetir motor di jalan dengan tanjakan dan turunan yang begitu curam. Rasanya tegang tapi juga seru. Setiap belokan seperti tantangan baru, membuatku harus lebih hati-hati mengatur gas dan rem. Namun, di balik gugup itu mataku dimanjakan oleh pemandangan yang luar biasa indah. Hamparan hijau perbukitan, langit biru yang terang, dan udara yang mulai terasa membuatku lupa sejenak pada panas dan debu tadi. Suasananya cantik dan benar-benar menenangkan hati.
Di tengah keindahan itu, pandangan kami tertuju pada suatu yang berbeda. Dari kejauhan, tampak area tambang batu bara, besar dan terbuka, kontras dengan hijau di sekitarnya. Debu dan warna tanah yang gelap membuat pemandangan sedikit terganggu. Aku terdiam sejenak, hanya bisa memandangi tempat itu sambil berfikir, betapa indahnya alam di sini, tapi juga betapa mudahnya keindahan itu berubah rusak ketika disentuh oleh tangan manusia.
Perjalanan yang panjang akhirnya membawa kami sampai di Sekolah Gajah. Rasa lega langsung muncul. Panas matahari terasa semakin menyengat dan angin yang berhembus membawa debu batu bara yang membuat udara terasa berat. Pemandangan yang tadinya begitu cantik dan menangkan perlahan berubah.
Keindahan perbukitan yang hijau kini tertutup debu halus yang menempel di kulit dan pakaian. Udara yang seharusnya segar kini bercampur dengan bau tanah dan panas yang menusuk.
Rasa lelah terbayarkan karena akhirnya kami tiba. Panas dan debu mungkin mengganggu, tetapi semangat untuk melanjutkan kegiatan di Sekolah Gajah tetap terasa kuat di dada. Hari mulai gelap. Setelah semua urusan di Sekolah Gajah selesai, kami bergegas untuk pulang. Namun kali ini, aku berboncengan dengan Miftah, katanya dia ingin naik motor karena sewaktu berangkat menuju bukit dia mabuk di mobil.
Sebelum kembali ke posko, kami sempat singgah ke sebuah tempat tertinggi yang tidak jauh dari Sekolah Gajah. Udara di sana terasa lebih sejuk, meski jalan menuju ke sana cukup menantang. Kami bahkan sempat tersesat, sebelum akhirnya bertemu lagi dengan teman-teman yang lain.
Dari tempat tertinggi itu, pandanganku langsung tertuju pada Bukit Serelo atau yang biasa disebut Gunung Jempol. Dari sini, bentuknya terlihat begitu jelas dan megah, seolah sedang diam mengamati kami dari kejauhan. Namun sebelum sampai ke puncak, mataku sempat menangkap pemandangan lain, area tambang batu bara yang luas dengan tanah terbuka dan warna gelap yang kontras dengan hijau perbukitan.
Dalam hati, aku sempat berfikir, kalau tambang batu bara itu tidak ada, pasti pemandangan ini jauh lebih indah.
Sesampainya di atas, kami pun berfoto bersama. Saat suasana mulai tenang, Mbak Nila mengingatkan untuk berfoto, siapa tahu ini terakhir kalinya kami melihat Bukit Serelo seperti ini.
“Soalnya, bukit ini nanti bakal jadi tambang batu bara,” ujarnya.
Kata-kata itu langsung membuatku terdiam. Aku menatap bukit yang perlahan mulai diselimuti senja. Rasanya sayang sekali keindahan sebesar ini, alam seindah ini, mungkin suatu hari nanti hanya tinggal kenangan.
Setelah semua selesai berfoto-foto, kami kembali ke posko. Badan rasanya sudah gerah dan tenaga mulai habis. Dalam hati aku meyakinkan diri sesampainya di posko mau langsung mandi.

Perjalanan terasa panjang hingga akhirnya kami sampai juga. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas ke kamar mandi, rasanya lega sekali saat air dingin menyentuh kulit, seolah semua lelah dan debu di tubuh ikut hilang terbawa air. Setelah selesai mandi, kami beristirahat sejenak. Aku sempat tertidur karena terlalu lelah.
Begitu terbangun, kulihat Kak Agung, Fathul, Miftah, Ridho, Reva, dan Jupio sedang menyiapkan tempat untuk memanggang sate di halaman. Aku pun ikut membantu mereka. Saat membantu, aku sempat merasa aneh. Walaupun malam, hawa panas masih terasa dan ada debu-debu halus di udara yang membuat hidung gatal dan nafas sedikit terganggu. Meski begitu, suasana tetap ramai dan menyenangkan.
Waktu memanggang selesai. Meski prosesnya lama, banyak keseruan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada tawa, canda dan kerja sama kecil yang membuat malam itu terasa hangat. Akhirnya, kami makan bersama teman-teman posko dan lainnya.
Setelah semua selesai makan, suasana menjadi semakin akrab. Kami saling berbincang dan bercanda, tertawa di antara sisa asap panggangan yang masih samar di udara. Rasanya menyenangkan, malam itu seperti jadi sempurna setelah perjalanan panjang yang melelahkan.
Waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Satu persatu mulai merasa mengantuk. Kami akhirnya memutuskan untuk beristirahat, karena besok masih ada kegiatan lain yang menunggu. Sebelum memejamkan mata, aku sempat berfikir sejenak tentang hari ini, tentang perjalanan, panas, tawa, dan semua hal kecil yang terasa berharga. Lelah memang, tapi di balik semua itu ada rasa syukur yang tidak bisa dijelaskan.
Di tengah malam, aku tiba-tiba terbangun. Tubuhku terasa panas dan penuh dengan keringat. Aku sempat kaget karena rasanya aneh. Padahal aku tidurnya di lantai tanpa memakai baju agar lebih terasa dingin. Dalam keadaan masih mengantuk, aku duduk perlahan sambil mengusap wajah. Keringat membasahi tubuhku dan aku heran sendiri. Udara malam seharusnya dingin, tapi entah kenapa terasa begitu gerah malam itu.
Mataku sempat melihat sekeliling, teman-teman lain masih tertidur lelap. Aku menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri, lalu berbaring lagi sambil terus bertanya-tanya kenapa panasnya sampai begini.
Jembatan Gantung dan Cerobong PLTU
Pagi tiba, udara terasa sedikit dingin. Dinginnya menusuk tapi justru membuat semangatku kembali hidup. Kami semua bangun perlahan, lalu mandi bergantian. Air pagi yang dingin seperti membangunkan seluruh sendi tubuh, menyapu sisa lelah semalam. Setelah semuanya rapi, kami bersiap untuk menjalankan hari itu. Sebelum berangkat, kami sarapan bersama, suasana hangat dan akrab, tawa kecil terdengar di sela-sela sendok yang beradu dengan piring.
Begitu selesai makan, kami berangkat menuju tempat tujuan. Langkah kami menuntun ke sebuah jembatan gantung yang membentang di atas Sungai Lematang. Saat menapaki jembatan itu, rasanya seperti ditarik kembali ke masa kecil. Aku diam sejenak, dejavu menyeruak. Dulu, aku juga sering menyeberangi sungai lewat jembatan gantung seperti ini di kampungku.
Angin berhembus, membuat jembatan sedikit bergoyang. Terlihat dari kejauhan cerobong asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjulang di seberang jembatan. Asap putih keabu-abuan keluar perlahan, menari di udara yang sudah tampak buram. Aku pastikan inilah penyebab udara kotor di wilayah ini. Pantas saja kemarin aku susah bernafas.
Setelah selesai menyeberang, kami langsung melaksanakan kegiatan. Semua tampak sibuk dengan tugasnya masing-masing, ada yang wawancara, dan ada juga yang mulai mendokumentasikan kegiatan. Udara panas terasa begitu menyengat, membakar kulit, hingga peluh terus menetes tanpa henti. Panas itu justru seperti bahan bakar yang menyalakan semangat kami. Tidak ada yang mengeluh, semua tetap berusaha tersenyum dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Panas matahari mungkin menguji tubuh kami, tapi semangat kami jauh lebih dari itu.
Matahari sudah tepat di atas kepala. Panasnya semakin menjadi-jadi seperti tidak memberi ampun sedikit pun. Udara terasa berat, keringat mengalir tanpa henti sampai membuat baju kami benar-benar basah. Aku menatap Miftah sambil menarik ujung bajuku yang menempel di badan.
“Mif, lihat bajuku sampai basah,” ujarku setengah tertawa tapi juga kelelahan.
Hari semakin siang dan perlahan beranjak menuju sore. Panas matahari mulai sedikit mereda, dan kami memutuskan untuk kembali ke posko untuk beristirahat dan makan siang. Sesampainya di posko, kaki seperti mati rasa, badan lengket oleh keringat dan debu.
Kami duduk terdiam sejenak, mencoba menenangkan nafas sambil mengeringkat keringat di wajah. Tidak lama kemudian, kami pun bersiap-siap untuk mandi secara bergantian. Air dingin menyentuh kulit terasa begitu menyegarkan, seolah semua lelah tadi perlahan ikut larut. Setelah semua selesai mandi, kami makan siang bersama dengan suasana santai. Canda kecil dan rawa ringan mengisi ruangan menutup hari.
Usai makan, kami beristirahat sebentar. Beberapa di antara kami tertidur, sementara yang lain hanya bersandar sambil sambil memainkan ponsel. Setelah tubuh kembali sedikit segar, kami berencana berjalan sore, menikmati udara desa yang teduh, sambil melihat aktivitas warga di Desa Muara Maung tempat kami tinggal.
Sore pun tiba. Langit mulai berwarna jingga dan udara terasa sedikit lebih sejuk. Kami berjalan berkeliling menikmati suasana Desa Muara Maung yang perlahan mulai ramai. Di lapangan kecil, anak-anak tampak berlarian riang bermain bola, tertawa tanpa beban. Di sisi lain, para remaja dan orang dewasa sibuk bermain voli, sementara beberapa warga berjualan makanan di pinggir jalan, menata dagangan mereka dengan wajah cerah meski debu masih beterbangan.
Aku sempat terdiam sejenak, memandangi mereka dari kejauhan. Dalam hati aku berkata pelan, “Bagaimana keadaan mereka, ya? Setiap hari menghirup udara kotor akibat PLTU dan tambang batu bara.” Pikiran itu membuat dadaku menghangat sekaligus sesak, ada kagum pada semangat mereka dan iba yang sulit dijelaskan.
Menjelang malam, kami pulang ke posko dan bersiap makan malam. Saat berjalan, aku menatap langit yang mulai kelabu. Awan tampak menggumpal dan angin berhembus lembut membawa aroma tanah. “Alhamdulillah, mau turun hujan,” ujarku sambil tersenyum kecil.
Setelah membersihkan diri seadanya, kami makan malam bersama. Sambil makan, obrolan ringan mulai mengalir. Di tengah percakapan, Mbak Nila menyarankan agar kami ke jalan besar sekitar pukul 22.00 WIB. Di sana biasanya banyak truk batu bara melintas. Kami pun menyanggupi. Selesai makan, waktu masih cukup luang. Kami duduk-duduk di ruang tengah, mengobrol santai sambil menunggu jam yang dimaksud. Suasananya hangat, capek, tapi tetap ada tawa di sela-selanya.

Ketika waktunya tiba, aku, Fathul, Reva, Ridho, dan Miftah berangkat menuju jalan besar. Jaraknya tidak terlalu jauh dari posko, hanya perlu berjalan beberapa menit. Sesampainya di sana, aku langsung terdiam. Kaget melihat di depan kami, truk-truk besar melintas tanpa henti, membawa muatan batu bara. Jumlahnya banyak sekali. Deru mesinnya keras dan setiap truk lewat, debu jalanan langsung terangkat, menyebar ke udara dan masuk ke hidung. Kami berlima refleks menutup hidung sambil merekam apa yang kami lihat.
“Beehh… debunya,” gumamku sambil menggeleng membayangkan bagaimana anak-anak yang tinggal di sini setiap hari.
Belum sempat mengamati, hujan mulai turun. Rintiknya rapat, kami langsung bergegas pulang. Meski hujan, hawa panas masih terasa jelas. Bukannya dingin, malah seperti uap panas yang naik dari tanah.
Di perjalanan pulang, rasa takut mulai muncul, pikiran macam-macam datang begitu saja. Hujan yang bercampur dengan debu PLTU, debu jalanan, dan debu tambang batu bara, entah apa yang sebenarnya turun malam itu. Rasanya tidak menenangkan sama sekali. Kami sampai di posko dalam keadaan sedikit basah dan lelah. Teman-teman lain sudah beristirahat lebih dulu karena besok jadwal pulang ke Palembang.
- Cerita Inspiratif UMKM Tekstil Ramah Lingkungan Asal Bekasi Bangkit dari Kegagalan Berkat BRI
- Wayang Palembang Tampil di OPI Mall: Upaya Lestarikan Warisan Budaya untuk Generasi Muda
- Komitmen Iklim Indonesia di COP 30 Minim Keadilan Bagi Perempuan
Aku berbaring dan bersiap untuk tidur. Namun, sebelum tidur mataku benar-benar terpejam, satu pikiran kembali muncul, kali ini lebih kuat dari sebelumnya tentang bagaimana keadaan mereka semua yang di sini selama ini.
Perjalanan singkat itu akhirnya membuka mataku tentang banyak hal. Bukan hanya tentang panas, debu, atau jauhnya perjalanan, tapi tentang kehidupan orang-orang yang menjalaninya setiap hari. Kami hanya merasakan semua itu dalam hitungan hari, sementara mereka hidup bersama udara yang sama, jalanan yang sama, dan risiko yang sama tanpa pernah benar-benar punya pilihan.
Saat perjalanan pulang ke Palembang, aku berkali kali memandangi jalanan dari jendela dan teringat anak-anak di Muara Maung dan desa-desa di sebelahnya, warga yang menyapa kami dengan senyum, serta tambang batu bara yang berdiri tepat di depan mata.
Aku sadar, pulang tidak berarti melupakan. Pengalaman ini membuatku bertanya-tanya, apa yang bisa kami lakukan?
*Mahasiswa Prodi Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang, Angkatan 2023